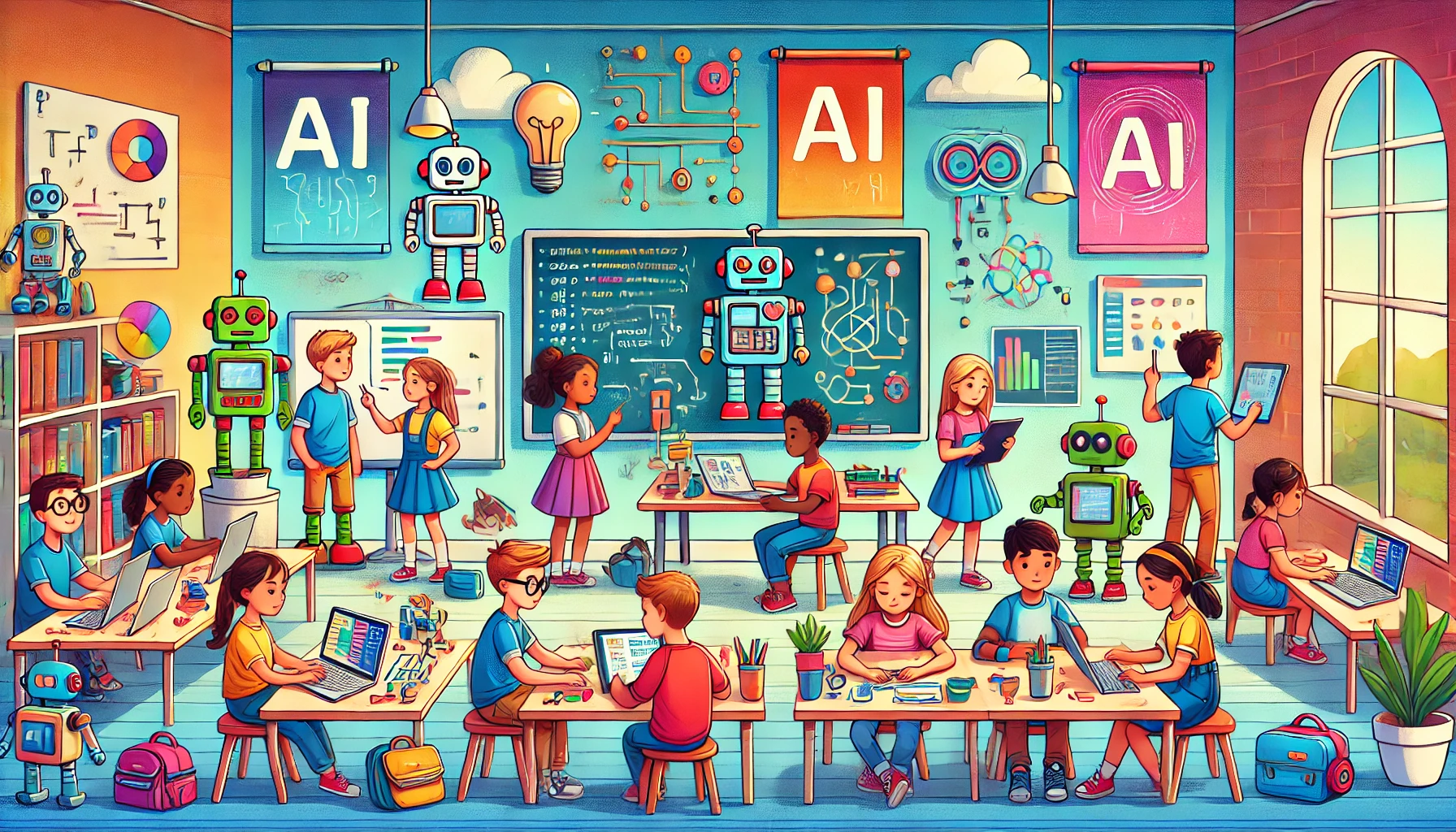Monitorday.com – Sejak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencanangkan program pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) untuk sekolah dasar hingga menengah, respon publik cukup beragam.
Di satu sisi, langkah ini dinilai progresif dan visioner. Namun di sisi lain, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan urgensinya, terutama jika dikaitkan dengan kondisi riil pendidikan Indonesia. Sejumlah kritik pun muncul—dari keterbatasan infrastruktur hingga ketakutan akan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan.
Namun benarkah semua kritik itu menggambarkan realitas program ini secara utuh?
Berikut adalah lima kesalahpahaman umum atau salah kaprah yang kerap muncul terkait program Koding dan KA di sekolah. Penjelasan ini berdasarkan Naskah Akademik resmi serta kebijakan pemerintah.
1. Sekolah Belum Siap, Tapi Dipaksa Mengajar AI dan Koding
Faktanya, program ini tidak bersifat wajib. Dalam Naskah Akademik Pembelajaran Koding dan KA yang dirilis Februari 2025, disebutkan bahwa implementasi hanya dilakukan di sekolah yang telah memenuhi syarat kesiapan infrastruktur dan SDM. Program ini juga bersifat fleksibel yakni bisa masuk sebagai pelajaran pilihan, integrasi dengan mapel lain, atau kegiatan ekstrakurikuler.
Menjadikan koding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan bisa dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan 3 aspek: ketersediaan guru pengampu, ketersediaan sarana dan prasarana serta kesediaan sumber belajar.
2. Program Ini Akan Menggantikan Pelajaran Dasar seperti Matematika dan Bahasa
Ini juga tidak benar. Program Koding dan KA dirancang sebagai tambahan wawasan abad ke-21, bukan pengganti literasi dan numerasi. Kegiatan pembelajaran tetap memberi ruang prioritas pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung.
Dalam desain kurikulum, pelajaran ini hanya dijadwalkan selama 2 jam pelajaran per minggu untuk kelas 5–10 dan maksimal 4–5 jam untuk jenjang lanjutan (SMA/SMK kelas 11–12). Bahkan, sekolah diberikan keleluasaan penuh apakah ingin mengintegrasikan ke dalam mapel eksisting seperti informatika atau menjadikannya kegiatan tambahan.
3. Siswa Disuruh Koding Padahal Belum Bisa Membaca
Kritik ini muncul dari asumsi bahwa siswa akan langsung diperkenalkan pada bahasa pemrograman yang rumit. Padahal, pendekatan utama yang digunakan adalah penguatan “berpikir komputasional”, bukan teknis koding semata.
Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun langkah sistematis, memecah masalah, dan menciptakan solusi. Ini bisa diterapkan lewat permainan logika, kegiatan berbasis cerita, hingga aktivitas unplugged yang tidak memerlukan komputer. Bahkan di tingkat SD, siswa tidak langsung diajarkan bahasa pemrograman, melainkan diajak mengenal pola dan struktur berpikir logis.
4. AI Akan Menggantikan Peran Guru dan Mengikis Nilai Kemanusiaan
Sebaliknya, program ini justru mengedepankan penguatan nilai-nilai etis dalam penggunaan teknologi. Salah satu pilar dalam Naskah Akademik adalah literasi etika digital—termasuk isu privasi, keamanan data, dan penggunaan AI secara bertanggung jawab.
Dalam berbagai pelatihan dan modul yang disusun, guru dibekali pemahaman agar siswa tidak hanya “terampil memakai”, tetapi juga “bijak memanfaatkan”. Bahkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa AI harus menjadi alat bantu berpikir, bukan pengganti akal sehat atau empati manusia.
5. Guru Dibiarkan Mengajar Tanpa Bekal
Justru sebaliknya. Pemerintah menjalankan pelatihan berskala nasional dalam bentuk Training of Trainers (ToT) dan Bimbingan Teknis. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 2.700 guru dari berbagai provinsi telah terlibat dalam pelatihan yang mencakup kompetensi teknis dan pedagogi.
Pelatihan berlangsung secara modular dan terstandar, disertai dengan pendampingan praktik langsung di sekolah. Guru tidak hanya diajarkan materi, tapi juga cara menyampaikan dengan pendekatan kontekstual dan menyenangkan.
Kesimpulan
Program pembelajaran Koding dan KA memang bukan tanpa tantangan. Kesenjangan infrastruktur, disparitas mutu guru, dan potensi resistensi lokal tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Namun banyak dari kritik yang beredar justru lahir dari kesalahpahaman atas konsep dasar dan pendekatan program ini.
Langkah Kemendikdasmen memperkenalkan literasi digital dan etika teknologi sejak dini patut diapresiasi, asalkan dilakukan secara bertahap, adil, dan adaptif terhadap konteks lokal.
Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, menunda inovasi bukanlah pilihan bijak. Tapi membabi buta tanpa kesiapan juga bukan jalan keluar. Seperti coding itu sendiri—program ini perlu logika, struktur, dan evaluasi terus-menerus.