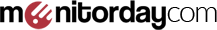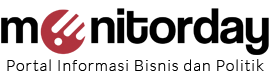SWEDIA dikenal sebagai negeri yang berhasil memadukan keindahan alam dengan kecanggihan teknologi. Stockholm, ibu kota negara ini, adalah salah satu pusat inovasi dunia, rumah bagi unicorn teknologi seperti Spotify dan Klarna. Di sisi lain, Swedia juga terkenal dengan pendekatan kesejahteraannya yang khas: mengutamakan kesetaraan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Namun, seperti pepatah “tak ada gading yang tak retak,” Swedia juga menghadapi tantangan besar di tengah pesatnya arus digitalisasi. Salah satu pelajaran menarik dari Swedia adalah bagaimana negara ini mulai mengurangi ketergantungannya pada teknologi digital di sektor pendidikan — suatu langkah yang tampak kontradiktif dengan reputasinya sebagai pemimpin teknologi. Lantas, apa yang membuat Swedia memilih jalur ini, dan apa yang bisa kita pelajari dari keputusan tersebut?
Swedia, yang sebelumnya menjadi salah satu negara pelopor dalam adopsi teknologi pendidikan, mulai merasakan dampak negatif dari digitalisasi yang berlebihan di ruang kelas. Penelitian menunjukkan bahwa hasil akademik siswa menurun seiring meningkatnya penggunaan perangkat digital di sekolah. Keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung justru mengalami penurunan, sementara tingkat gangguan fokus dan kecemasan pada siswa meningkat.
Salah satu langkah kontroversial yang diambil Swedia adalah kembali ke penggunaan buku cetak dan mengurangi ketergantungan pada tablet dan laptop. Menteri Pendidikan Swedia bahkan menyatakan bahwa pendidikan berbasis teknologi tidak selalu menjamin hasil yang lebih baik. Kebijakan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Universitas Uppsala, yang menemukan bahwa pembelajaran melalui buku cetak meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dibandingkan dengan membaca di layar digital.
Langkah Swedia ini menarik perhatian dunia. Di tengah gempuran narasi global yang mendorong digitalisasi tanpa batas, Swedia justru mengambil langkah mundur — atau mungkin lebih tepatnya, lompatan maju — untuk mengevaluasi kembali prioritas pendidikan mereka. Tetapi apa sebenarnya nilai dasar pendidikan yang ingin dijaga oleh Swedia?
Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan. Ia adalah proses pembentukan karakter, pengembangan keterampilan hidup, dan penciptaan individu yang mampu berkontribusi pada masyarakat. Nilai-nilai dasar pendidikan meliputi literasi, numerasi, pemikiran kritis, etika, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman.
Swedia, seperti banyak negara Eropa lainnya, memiliki tradisi pendidikan yang kuat berbasis pada nilai-nilai ini. Namun, digitalisasi yang terlalu cepat cenderung mengaburkan fondasi tersebut. Anak-anak lebih sering terpaku pada layar, sementara interaksi sosial, pendidikan karakter, dan keterampilan hidup mulai tergeser oleh algoritma dan aplikasi.
Langkah Swedia untuk kembali ke buku cetak dan metode pembelajaran tradisional adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan ini. Mereka menyadari bahwa teknologi, meskipun penting, tidak dapat menggantikan peran guru dalam membentuk karakter siswa atau menciptakan suasana belajar yang humanis.
Langkah Swedia mengingatkan kita bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar. Teknologi harus menjadi pendukung, bukan pengganti, nilai-nilai dasar pendidikan. Di sini, teori “Human-Centered Design” dari Don Norman relevan untuk dijadikan acuan. Norman menekankan bahwa teknologi harus dirancang untuk melayani kebutuhan manusia, bukan manusia yang beradaptasi dengan teknologi.
Sebagai contoh, teknologi dapat digunakan untuk mendukung personalisasi pembelajaran melalui analisis data. Namun, teknologi ini harus diterapkan secara bijak, tanpa mengorbankan interaksi langsung antara guru dan siswa. Pendekatan blended learning, yang menggabungkan teknologi dengan metode tatap muka, mungkin menjadi solusi yang ideal.
Selain itu, literasi digital juga perlu ditekankan sebagai bagian dari kurikulum. Siswa perlu diajarkan untuk menggunakan teknologi secara kritis, memahami dampaknya terhadap kehidupan, dan mengenali informasi palsu di era post-truth ini. Dalam hal ini, Swedia menunjukkan bahwa mengurangi ketergantungan pada teknologi tidak berarti menolak digitalisasi sepenuhnya, melainkan mencari keseimbangan yang sehat.
Indonesia, dengan tantangan geografis dan demografis yang unik, dapat mengambil pelajaran berharga dari langkah Swedia. Di satu sisi, digitalisasi sangat membantu menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan akses pendidikan. Namun, kita juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam euforia teknologi yang justru mengorbankan kualitas pendidikan.
Program digitalisasi perlu terus dievaluasi agar tetap berpijak pada nilai-nilai dasar pendidikan. Literasi dan numerasi harus menjadi prioritas, terutama di jenjang pendidikan dasar. Selain itu, pendidikan karakter harus tetap menjadi inti dari setiap kurikulum, dengan guru memegang peran sentral sebagai fasilitator dan inspirator.
Seperti halnya Swedia, Indonesia juga perlu mencari keseimbangan antara inovasi dan tradisi. Digitalisasi dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong pemerataan pendidikan, tetapi teknologi tidak boleh menjadi “pengganti” dari apa yang membuat pendidikan bermakna: interaksi manusia, pengajaran nilai, dan pembentukan karakter.
De-digitalisasi pendidikan di Swedia bukan sekadar langkah mundur, melainkan refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam pendidikan. Teknologi, meskipun penting, hanyalah alat. Nilai-nilai dasar pendidikan — literasi, numerasi, etika, dan keterampilan hidup — adalah fondasi yang harus dijaga.
Dalam dunia yang semakin kompleks, kita membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi tetapi juga memiliki karakter kuat dan kemampuan berpikir kritis. Untuk mencapainya, kita harus terus mencari keseimbangan antara inovasi dan tradisi, seperti yang telah ditunjukkan oleh Swedia. Inilah pelajaran berharga yang tidak boleh kita abaikan.