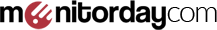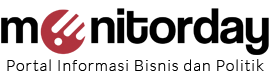Monitorday.com – Pergeseran kekuasaan dalam dunia politik sering kali dipahami sebagai suatu hal yang tak terhindarkan. Seiring berjalannya waktu, berbagai dinamika politik mengarah pada perubahan-perubahan yang tidak selalu dapat diprediksi.
Namun, ada kalanya suatu jabatan justru menjadi begitu melekat pada diri seseorang, seolah-olah tak terlepaskan, menciptakan ilusi bahwa jabatan tersebut adalah bagian dari takdir politik individu tersebut. Fenomena ini kerap tampak jelas dalam tindakan atau pernyataan politisi yang merasa tidak terpisahkan dari posisi yang mereka pegang.
Kita bisa melihat dengan jelas sikap diplomatis yang diambil oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, yang dengan hati-hati menyampaikan pernyataan tentang tak rasionalnya seseorang yang ingin memimpin PPP tanpa memahami seluk-beluk internal partai tersebut.
Pernyataan Mardiono, yang menegaskan bahwa tidak mungkin ada orang yang akan memimpin PPP tanpa memahami dinamika dan karakteristik politik partai tersebut, mengundang banyak tafsiran.
Ada kesan bahwa Mardiono ingin menjaga kekuasaannya dengan cara yang lebih halus, menghalangi kemungkinan calon lain yang belum mengenal secara mendalam struktur dan budaya partai untuk merebut posisi tersebut.
Pernyataan ini tampaknya menggarisbawahi ketergantungan pada jabatan yang telah ia duduki, sebuah posisi yang dalam pandangannya mungkin terlalu kompleks untuk dikuasai oleh pihak luar yang tidak mengerti konteks internal partai.
Dalam perspektif sastra kritis, kita bisa melihat sikap Mardiono sebagai sebuah bentuk pemeliharaan kekuasaan melalui wacana yang berputar di sekitar konsep keahlian dan kedalaman pengetahuan.
Dengan membingkai kepemimpinan sebagai sebuah kapasitas yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah “menyatu” dengan budaya partai, ia seolah-olah menciptakan sebuah narasi eksklusif yang mengunci ruang bagi siapa pun yang dianggap asing.
Ini menjadi semacam mitos politik yang meneguhkan bahwa hanya mereka yang terlahir dalam lingkaran tertentu yang memiliki legitimasi untuk memimpin, sementara yang lain hanya dianggap sebagai outsider yang tidak layak memimpin.
Pada saat yang sama, pernyataan tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan mendalam tentang sejauh mana sebuah jabatan bisa membentuk identitas seorang pemimpin. Dalam literatur sastra, identitas seringkali dilihat sebagai sesuatu yang terbentuk dari interaksi antara individu dengan dunia sekitarnya.
Dalam hal ini, jabatan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP telah menjadi bagian integral dari identitas politiknya. Seiring dengan waktu, jabatan tersebut tidak hanya memberi pengaruh, tetapi juga memberikan sebuah pengakuan yang semakin sulit untuk dilepaskan. Sebuah posisi yang, dalam perspektifnya, tidak hanya menawarkan kekuasaan, tetapi juga sebuah legitimasi sosial yang mendalam.
Namun, ada paradoks yang muncul dalam proses ini. Ketika seorang pemimpin merasa nyaman dengan posisi yang memberikan pengaruh dan pengakuan, seringkali ia menjadi semakin terikat oleh posisi tersebut, menjadikannya sulit untuk melihat atau menerima kemungkinan adanya perubahan. Fenomena ini mirip dengan apa yang disebut dalam sastra sebagai “kejatuhan tragis”—sebuah proses yang dimulai dengan rasa percaya diri yang tinggi, namun berujung pada keterjebakan dalam zona nyaman yang pada akhirnya menutup peluang untuk pembaruan.
Di sinilah muncul pertanyaan tentang sejauh mana Mardiono benar-benar berkomitmen pada prinsip-prinsip yang lebih besar, atau apakah ia sekadar menjaga status quo demi kepentingan pribadi.
Bagi sebagian pihak, sikap Mardiono yang enggan membuka ruang bagi calon ketua umum lain bisa dipandang sebagai tindakan yang memperlihatkan ketidakmauan untuk berbagi kekuasaan. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa pemegang kekuasaan lebih mementingkan kestabilan pribadi daripada stabilitas partai secara keseluruhan.
Dalam pandangan ini, pernyataan-pernyataan Mardiono seolah menjadi usaha untuk membangun narasi di mana ia adalah satu-satunya figur yang paling tepat untuk memimpin, karena pemahaman mendalam yang dimilikinya tentang internal PPP.
Namun, di balik sikap ini, terdapat pula fragmen-fragmen kekuasaan yang tidak tampak di permukaan. Dalam sastra, kekuasaan sering kali digambarkan sebagai sesuatu yang rapuh dan mudah retak jika terlalu bergantung pada individu tertentu. Ketergantungan pada satu sosok bisa membatasi kreativitas dan pembaruan dalam struktur yang lebih besar. Mungkin Mardiono tidak menyadari bahwa dengan terlalu mempertahankan posisinya, ia berisiko menciptakan kesenjangan antara dirinya dengan anggota partai lainnya, yang pada akhirnya bisa berujung pada disintegrasi internal yang tidak diinginkan.
Pernyataan-pernyataan Mardiono, meski penuh dengan alasan yang tampaknya logis, menyentuh sebuah dilema klasik dalam dunia politik: ketergantungan pada kekuasaan yang lama bisa menjadi penghalang bagi kemajuan yang baru. Fenomena ini mengingatkan kita pada kisah-kisah dalam sastra klasik, di mana tokoh utama sering kali terperangkap dalam jaring-jaring kebesaran dan kejayaannya sendiri.
Ketika sebuah jabatan menjadi terlalu menyenangkan, itu mungkin bukan lagi soal pengabdian kepada masyarakat atau tujuan lebih besar, melainkan lebih tentang mempertahankan posisi demi kenyamanan pribadi.
Dalam konteks ini, Mardiono, seperti tokoh-tokoh dalam sastra yang tak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, mungkin harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan yang terlalu lama dipegang bisa membelenggu langkah perubahan yang diperlukan dalam partainya.