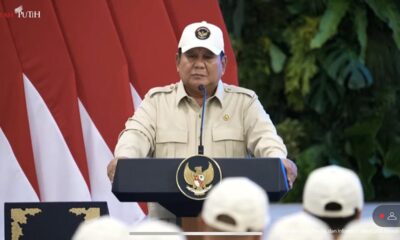Monitorday.com- Namanya Danantara, singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Lembaga ini diperkenalkan ke publik global dalam ajang World Economic Forum, menandai keseriusan Indonesia untuk tampil bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pemain strategis dalam peta ekonomi dunia. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Danantara diposisikan sebagai instrumen penting untuk mengakselerasi langkah Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Secara konsep, Danantara adalah sovereign wealth fund. Namun, pendekatan yang diambil jauh dari kesan konvensional. Jika banyak lembaga sejenis di dunia hanya berfokus pada imbal hasil investasi, Danantara mengusung mandat ganda: mengejar keuntungan ekonomi sekaligus menciptakan dampak sosial yang nyata. Artinya, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari angka neraca keuangan, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
Struktur Danantara dirancang untuk menjawab tantangan tersebut. Di satu sisi, terdapat lengan pengelolaan aset yang menaungi dan merapikan portofolio BUMN. Di sisi lain, ada lengan investasi yang bertugas menjadi motor pertumbuhan melalui penempatan modal strategis. Saat ini, lebih dari seribu entitas BUMN berada dalam proses konsolidasi agar menjadi lebih ramping, efisien, dan profesional. Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma: negara tidak lagi sekadar memiliki banyak perusahaan, tetapi ingin memastikan perusahaan-perusahaan itu sehat dan berdaya saing.
Arah investasi Danantara pun tidak dilepaskan dari kebutuhan riil bangsa. Fokus diberikan pada sektor-sektor yang menyentuh kehidupan banyak orang, seperti energi terbarukan, kesehatan, pangan, pertanian, infrastruktur, dan mineral. Pilihan ini menunjukkan bahwa investasi dipandang sebagai alat pembangunan, bukan sekadar instrumen finansial. Salah satu contoh konkret adalah program pengolahan sampah menjadi energi di puluhan kota. Masalah sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan diubah menjadi peluang ekonomi sekaligus solusi sosial.
Di sektor kesehatan, Danantara masuk ke investasi pengembangan obat turunan plasma darah. Langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian nasional di bidang kesehatan, terutama setelah pandemi membuka mata banyak negara tentang rapuhnya rantai pasok global. Bahkan sektor pelayanan ibadah pun tidak luput dari perhatian, melalui pengembangan kawasan Kampung Haji di Makkah untuk meningkatkan kualitas layanan jamaah Indonesia. Semua ini memperlihatkan bahwa investasi bisa hadir di ruang-ruang yang selama ini jarang dilihat sebagai bagian dari strategi ekonomi.
Salah satu agenda paling krusial Danantara adalah reformasi BUMN. Targetnya tidak main-main: memangkas jumlah entitas dari lebih 1.000 menjadi sekitar 200 perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Ini bukan sekadar penggabungan administratif, tetapi upaya membangun tata kelola baru yang lebih profesional. Penghapusan bonus bagi komisaris non-eksekutif, misalnya, menjadi sinyal bahwa efisiensi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon. Pembentukan holding sektoral, seperti holding rumah sakit, juga menunjukkan keseriusan untuk menempatkan kompetensi sebagai dasar pengelolaan.
Dari sisi skala, Danantara langsung mencuri perhatian. Dengan aset kelolaan sekitar 900 miliar dolar AS, lembaga ini masuk jajaran 10 besar sovereign wealth fund dunia. Fasilitas kredit sebesar 10 miliar dolar AS yang berhasil dihimpun menjadi bukti awal kepercayaan investor. Namun, besarnya angka juga membawa ekspektasi tinggi. Investor global menuntut konsistensi, transparansi, dan kepastian tata kelola, bukan sekadar narasi ambisius.
Danantara memang masih sangat muda. Usianya baru hitungan bulan, tetapi beban yang dipikulnya sangat besar. Ia dituntut bergerak cepat, namun tidak boleh tergesa. Di sinilah tantangan utamanya: menjaga keseimbangan antara keberanian mengambil peluang dan kehati-hatian dalam mengelola aset negara.
Pada akhirnya, Danantara adalah taruhan jangka panjang Indonesia. Keberhasilannya tidak akan terlihat dalam satu atau dua tahun, tetapi akan menentukan arah ekonomi nasional dalam beberapa dekade ke depan. Jika dikelola dengan disiplin dan keberpihakan pada kepentingan publik, Danantara berpotensi menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengelola kekayaannya sendiri secara modern, profesional, dan berkeadilan. Masa depan Indonesia, pada titik tertentu, akan sangat ditentukan oleh bagaimana lembaga ini bekerja hari ini.