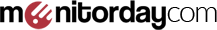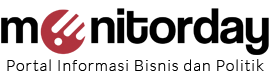Review
Tukang Kayu

Review
Strategi Global, Dimana Posisi Indonesia?
Di tengah eskalasi geopolitik antara Amerika, Israel, Iran, dan BRICIS, Indonesia harus segera menentukan arah strategisnya agar tetap relevan dan diperhitungkan dalam perubahan tatanan dunia.
Review
Jika Pilpres di 2026: Prabowo-Dedi Mulyadi, Duet Paling Tepat!
Jika Pilpres dipercepat pada 2026, duet Prabowo Subianto dan Dedi Mulyadi adalah pilihan ideal. Kombinasi ketegasan dan kerja nyata mereka menjawab harapan publik akan pemimpin yang tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak.
Review
Lebaran Usai, Janda Muda Meroket
Setelah Lebaran 2025, Indonesia mengalami lonjakan jumlah janda muda akibat peningkatan perceraian, terutama di Jawa Barat, dengan perselisihan dan masalah ekonomi sebagai penyebab utama.
Review
Ketika Hukum Diperjualbelikan, Tunggulah Kehancuran
Kasus suap hakim dalam vonis bebas Ronald Tannur mengungkap bobroknya sistem peradilan, mencerminkan krisis moral dan integritas yang mendalam.
Review
Israel! The Real Betrayer Till the end of the World
Israel berkali-kali mengingkari janji gencatan senjata, menggunakan strategi manipulasi untuk menipu masyarakat internasional. Dengan framing yang terencana, Israel terus melanjutkan agresi meski mengklaim ingin berdamai.
Review
Revolusi Energi! Bioavtur Minyak Jelantah Siap Mengudara
Pertamina mulai uji coba produksi bioavtur berbahan minyak jelantah di Kilang Cilacap dengan target 9.000 barel per hari, membuka era baru energi hijau bagi industri penerbangan Indonesia.
Review
Shahid Khan: Dari Cuci Piring ke Miliarder
Shahid Khan, pengusaha muslim Amerika, memulai kariernya sebagai pencuci piring sebelum sukses di industri otomotif dan olahraga. Kini, ia memiliki kekayaan 12,2 miliar dolar AS.
Review
Bantu Mudik di Indonesia? Putin Kabarnya Bakal Kirim Kapal Selam Supersonik
Putin ingin mengirim kapal selam supersonik untuk membantu pemudik motor di Indonesia yang selalu terjebak macet. Ide nyeleneh ini menggambarkan realitas transportasi kita yang absurd.
Review
Trump Mau Kirim Kapal Induk Bantu Lerai Kemacetan Mudik 2025? Lantas Putin…
Tradisi mudik Indonesia memang unik. Meski macet selalu jadi bumbu utama, rakyat tetap sabar dan kreatif. Trump mau bantu? Lucu, tapi hanya bisa terjadi di imajinasi.
Review
Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan dan Tantangan
MBG menjanjikan solusi gizi nasional dengan tambahan anggaran besar, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas, pengawasan, dan sumber dana. Sukses atau gagal? Semua tergantung eksekusi.