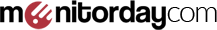Ruang Sujud
Zuhud di Era Digital: Menjadi Hamba yang Merdeka dari Dunia
Published
1 week agoon
By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com -;Dalam sejarah spiritualitas Islam, zuhud selalu menjadi sikap yang dimuliakan. Ia bukan sekadar praktik menjauhi dunia, tetapi sebuah kesadaran mendalam bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Di era digital yang serba cepat dan penuh godaan ini, zuhud bukan kehilangan makna, justru semakin relevan untuk menjaga kebeningan hati dan keteguhan iman.
Zuhud secara sederhana dapat dimaknai sebagai sikap tidak tergantung pada dunia, meskipun seseorang memilikinya. Bukan berarti seseorang harus meninggalkan harta, pekerjaan, atau kehidupan sosial. Zuhud bukan kemiskinan, tetapi kebebasan batin. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Zuhud itu bukan berarti kamu tidak memiliki apa-apa, tetapi kamu tidak diperbudak oleh apa yang kamu miliki.”
Kini, kita hidup di tengah kemewahan digital: gawai canggih, media sosial, aplikasi yang memanjakan, hingga budaya viral yang serba instan. Kita terhubung dengan dunia dalam sekejap, namun seringkali menjadi hamba dari layar yang ada di genggaman. Ketergantungan ini membuat zuhud terasa jauh dari kehidupan modern, padahal justru dibutuhkan lebih dari sebelumnya.
Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah overstimulation—banjir informasi, notifikasi tanpa henti, dan dorongan untuk selalu terlihat eksis. Inilah bentuk perbudakan modern yang halus: kita merasa harus terus merespon, terus mengikuti tren, terus membandingkan hidup dengan orang lain. Dalam situasi ini, zuhud hadir sebagai jalan pembebasan. Ia mengajak kita melepaskan keterikatan, bukan benda fisik semata, tapi juga ikatan mental terhadap pengakuan, validasi, dan pencitraan.
Zuhud di era ini bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil: membatasi waktu layar, mengurangi konsumsi media sosial, atau memilih untuk tidak mengikuti tren yang tak bermanfaat. Hal ini bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Dalam pandangan seorang zahid, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Ia tidak membiarkan hidupnya dikendalikan oleh algoritma, melainkan tetap menjaga ruh dan arah hidupnya dengan sadar.
Para ulama dahulu memberi contoh tentang bagaimana memiliki dunia tapi tidak mencintainya secara berlebihan. Umar bin Khattab, meski seorang pemimpin besar, tetap hidup sederhana dan tidak terikat pada kekayaan duniawi. Begitu pula Imam Hasan al-Bashri yang sangat meyakini bahwa ketenangan hanya didapat ketika hati tidak bergantung pada dunia. Dalam konteks hari ini, kita bisa meneladani mereka dengan cara menjadi pengguna teknologi yang beretika, tidak silau dengan gaya hidup digital yang penuh glamor, dan tetap menjadikan akhirat sebagai orientasi utama.
Menjadi zahid di era digital juga berarti mampu mengatakan “cukup” ketika dunia terus menawarkan “lebih”. Kita tidak harus selalu memiliki gadget terbaru, mengikuti gaya hidup influencer, atau merasa tertinggal saat tidak mengonsumsi hal-hal viral. Zuhud menanamkan rasa qana’ah—merasa cukup dengan yang ada. Dengan itu, hati menjadi tenang, dan hidup lebih fokus.
Lebih dari itu, zuhud melatih kita untuk hidup dengan kesadaran. Setiap interaksi digital seharusnya menjadi ladang amal, bukan ladang kesia-siaan. Kita bisa bertanya pada diri: apakah waktu yang saya habiskan di media sosial mendekatkan saya pada Allah? Apakah unggahan saya membawa manfaat atau sekadar pamer? Apakah saya menjadi hamba Allah, atau hamba dari likes dan komentar?
Dalam perspektif sufistik, zuhud adalah langkah awal menuju ma’rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Tanpa melepaskan diri dari keterikatan dunia, hati sulit menerima cahaya ilahi. Maka, siapa yang ingin naik derajat spiritual, ia harus rela membersihkan hatinya dari cinta dunia. Di zaman sekarang, cinta dunia itu bisa berbentuk obsesi pada popularitas digital, pencapaian semu, atau kemewahan virtual yang hanya tampak di layar.
Zuhud bukan pelarian dari kehidupan, tapi cara hidup yang jernih. Seorang zahid tetap bekerja, tetap bersosialisasi, bahkan bisa sukses di dunia, tapi hatinya tidak pernah tergantung padanya. Ia tidak sedih saat kehilangan, dan tidak bangga berlebihan saat mendapatkannya. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya.
Maka, menjadi zahid di era digital adalah perjuangan untuk tetap merdeka—merdeka dari keinginan tanpa batas, merdeka dari pencitraan, dan merdeka dari tekanan eksistensi virtual. Merdeka untuk memilih hidup yang bermakna, bukan yang sekadar terlihat menakjubkan di layar. Inilah esensi zuhud yang abadi: menjadikan dunia sebagai jembatan, bukan jebakan.
Zuhud di era digital memang tidak mudah. Tapi ia sangat mungkin, dan sangat dibutuhkan. Ia adalah benteng di tengah banjir informasi. Ia adalah oase di tengah hiruk-pikuk pencitraan. Dan yang terpenting, ia adalah jalan menuju kebebasan sejati—bebas dari dunia yang memperbudak, dan bebas untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih.
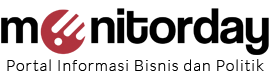
Mungkin Kamu Suka
Ruang Sujud
Iffah: Pilar Kekuatan Spiritual dalam Islam
Published
15 hours agoon
17/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Dalam ajaran Islam, kekuatan sejati tidak selalu diukur dari kekuasaan, harta, atau pengaruh sosial. Ada kekuatan yang lebih halus namun jauh lebih berpengaruh: kekuatan spiritual. Salah satu pilar utama kekuatan ini adalah iffah — sikap menjaga kehormatan diri dengan penuh kesadaran dan ketulusan.
Iffah berasal dari kata kerja ‘afafa, yang berarti menjaga diri, menahan nafsu, dan menghindari hal-hal yang dapat mengurangi kemuliaan pribadi. Dalam Al-Qur’an, Allah memuji orang-orang yang memiliki iffah, bahkan menganjurkan untuk membantu mereka, seperti dalam Surah An-Nur ayat 33: “Dan orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya yang tidak mampu menikah, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dari karunia-Nya.”
Dalam kehidupan sehari-hari, iffah menjadi fondasi bagi kekuatan batin yang kokoh. Orang yang memiliki iffah akan lebih mampu mengendalikan dirinya dalam situasi apa pun, tidak mudah tergoda oleh dunia, dan tetap teguh pada prinsip meski menghadapi godaan besar. Ini adalah kekuatan yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi terpancar dalam sikap, pilihan, dan kepribadian seseorang.
Dalam sejarah Islam, banyak tokoh besar yang membuktikan bahwa iffah adalah sumber kekuatan luar biasa. Salah satunya adalah Nabi Yusuf ‘alaihissalam, yang menjadi simbol kesucian diri dalam menghadapi godaan berat. Saat berhadapan dengan rayuan istri pembesar Mesir, Yusuf memilih mempertahankan kehormatannya meski risikonya adalah dipenjara. Kisah ini bukan sekadar cerita moral, tapi bukti nyata bahwa menjaga iffah adalah kemenangan besar dalam jihad melawan hawa nafsu.
Kekuatan iffah juga terlihat dalam keseharian Rasulullah ﷺ. Beliau adalah sosok yang selalu menjaga adab dalam interaksi, penuh kasih, tetapi tetap tegas dalam menjaga prinsip. Rasulullah mengajarkan bahwa harga diri manusia lebih berharga daripada dunia dan seisinya, dan iffah adalah salah satu cara menjaga harga diri itu tetap utuh.
Saat ini, di tengah zaman yang serba bebas, menjaga iffah bisa terasa sangat menantang. Kita hidup di era di mana batasan-batasan moral sering dipertanyakan, bahkan dihapus. Media sosial, hiburan, dan budaya populer seringkali mengaburkan mana yang pantas dan mana yang tidak. Dalam situasi seperti ini, memiliki iffah bukan hanya soal menjaga citra, tapi tentang mempertahankan identitas diri yang autentik sebagai seorang Muslim.
Menjaga iffah juga membawa banyak dampak positif dalam aspek kehidupan lainnya. Dalam hubungan sosial, seseorang yang ber-iffah akan lebih dihormati, dipercaya, dan diandalkan. Dalam hubungan keluarga, iffah memperkuat nilai kesetiaan, rasa hormat, dan kasih sayang yang tulus. Dalam dunia kerja, iffah menjauhkan seseorang dari praktik curang, korupsi, atau perilaku tidak etis lainnya.
Sikap iffah mengajarkan kita untuk menahan diri bukan karena takut dilihat orang, tapi karena sadar bahwa Allah selalu mengawasi. Ini menumbuhkan keikhlasan dalam hati, membangun hubungan yang lebih dalam dengan Allah, dan menguatkan keteguhan iman. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya’ Ulumuddin menulis bahwa iffah adalah bagian penting dari akhlak mulia yang menjadi jalan menuju kebahagiaan hakiki.
Lebih dari sekadar menjaga diri dari dosa, iffah mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, niat, dan sikap dari segala sesuatu yang bisa mengotori hati. Ini termasuk menjaga pandangan, menjaga ucapan, mengontrol emosi, dan menghindari niat buruk terhadap sesama. Semua ini, jika dijalani dengan konsisten, akan membentuk karakter pribadi yang luhur dan kuat.
Untuk menumbuhkan iffah, dibutuhkan kesadaran diri dan latihan yang terus menerus. Tidak cukup hanya mengandalkan keinginan sesaat. Seperti atlet yang berlatih setiap hari untuk mencapai performa terbaik, menjaga iffah juga perlu komitmen harian: memperbaiki niat, mengevaluasi diri, dan terus belajar dari kesalahan.
Lingkungan juga memegang peran penting. Berada di lingkungan yang positif, bersama orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan, akan sangat membantu menjaga iffah. Rasulullah ﷺ bersabda, “Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
Pada akhirnya, iffah adalah karunia dan perjuangan. Ia adalah anugerah bagi siapa pun yang mau berusaha menjaganya dengan kesungguhan. Orang yang hidup dengan iffah tidak hanya menjaga dirinya dari kehinaan, tetapi juga mempersiapkan dirinya untuk meraih kemuliaan di dunia dan akhirat.
Di tengah dunia yang semakin riuh dan penuh godaan, iffah adalah cahaya yang membimbing kita tetap berada di jalan yang lurus. Ia adalah pilar kekuatan spiritual yang akan membuat kita tetap berdiri tegak, meski badai ujian datang bertubi-tubi.
Dan ingat, menjaga iffah bukan berarti membatasi kebebasan, tapi justru memerdekakan diri dari perbudakan nafsu. Dengan iffah, kita menemukan martabat, menemukan makna hidup, dan menemukan cinta sejati dari Sang Pencipta.
Ruang Sujud
Iffah dalam Kehidupan Sehari-hari: Menemukan Keindahan dalam Menjaga Diri
Published
19 hours agoon
17/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, banyak nilai yang perlahan-lahan mulai terlupakan. Salah satunya adalah iffah, sikap menjaga kehormatan diri. Meski sering dipandang kuno, sebenarnya iffah justru menawarkan sebuah keindahan yang langka: ketenangan, martabat, dan rasa percaya diri yang sejati.
Iffah berasal dari kata ‘afafa yang berarti menahan diri dari hal-hal yang tidak pantas. Dalam Islam, iffah mencakup menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga perilaku, hingga menjaga kehormatan dalam relasi sosial. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang menuntut kesadaran tinggi, bukan sekadar mengikuti arus.
Bayangkan, di dunia yang serba bebas ini, seseorang yang mampu menjaga dirinya dari godaan, dari perilaku yang merendahkan harga diri, adalah sosok yang sangat berharga. Mereka seperti bunga yang tetap mekar indah di tengah gurun, tetap wangi meski lingkungan sekitarnya penuh debu.
Dalam kehidupan sehari-hari, iffah bisa tampak dalam banyak bentuk sederhana. Seorang mahasiswa yang memilih untuk tidak menyontek meski semua temannya melakukannya. Seorang karyawan yang menolak suap walau ada kesempatan besar. Seorang pemuda yang menahan pandangan saat melewati sesuatu yang menggoda di jalan. Hal-hal kecil ini, saat dikumpulkan, membentuk karakter besar: pribadi ber-iffah.
Menjaga iffah bukan berarti mengasingkan diri dari dunia, tapi justru bersikap cerdas dalam berinteraksi. Ketika seseorang menjaga lisan dari gibah dan fitnah, ia sedang membangun reputasi baik tanpa perlu memaksakan diri. Ketika ia memilih pakaian yang sopan, ia sedang menunjukkan rasa hormat pada dirinya sendiri dan pada orang lain.
Kehidupan sosial kita hari ini seringkali menormalisasi perilaku yang dulu dianggap tercela. Dari konten media sosial yang vulgar, budaya flexing harta secara berlebihan, sampai pergaulan bebas yang dianggap lumrah. Dalam situasi seperti ini, iffah menjadi semacam “perlawanan sunyi” — tidak dengan marah-marah, tapi dengan konsistensi menjaga nilai.
Tentu menjaga iffah itu berat, apalagi saat lingkungan sekitar seperti membiarkan semua batasan runtuh. Tapi justru di situlah keindahannya. Seperti berlian yang terbentuk dari tekanan luar biasa, seseorang yang tetap menjaga dirinya di tengah ujian akan bersinar dengan keindahan yang tidak mudah dipalsukan.
Kita bisa belajar banyak dari teladan para tokoh Islam yang luar biasa dalam menjaga iffah. Misalnya, Mariam binti Imran, ibu Nabi Isa ‘alaihissalam, yang terkenal akan kesucian dan keteguhannya. Dalam Al-Qur’an, ia disebut sebagai wanita pilihan yang menjaga dirinya dengan penuh kehormatan, hingga namanya diabadikan sebagai salah satu surah.
Bagi kita yang hidup di zaman ini, menjaga iffah bisa dimulai dari langkah kecil. Misalnya, memilih tontonan yang bersih, memperhatikan apa yang kita bagikan di media sosial, atau menghindari candaan-candaan yang menjurus pada hal negatif. Kadang kita merasa itu hal sepele, tapi semua kebiasaan kecil itu, lama-lama membentuk siapa diri kita sebenarnya.
Salah satu keindahan dari iffah adalah munculnya rasa damai dalam hati. Ketika kita tidak merasa harus berpura-pura, tidak harus mengikuti standar dunia yang terus berubah, kita jadi lebih bisa menikmati hidup apa adanya. Kita tidak sibuk membandingkan diri, tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu terlihat sempurna di mata orang lain.
Selain itu, orang yang menjaga iffah seringkali justru lebih dihormati, meskipun awalnya mungkin mereka dianggap “berbeda” atau “ketinggalan zaman”. Kehormatan yang dibangun atas dasar prinsip jauh lebih kokoh daripada popularitas sesaat. Orang lain bisa saja lupa dengan postingan viral atau tren singkat, tapi mereka akan selalu mengingat integritas seseorang.
Menariknya, menjaga iffah juga membuat hubungan antar manusia lebih sehat. Hubungan pertemanan, hubungan bisnis, bahkan hubungan percintaan menjadi lebih tulus karena dibangun atas dasar saling menghormati, bukan saling mengeksploitasi. Dengan iffah, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga orang lain dari perbuatan yang bisa menodai martabat mereka.
Dalam skala yang lebih luas, masyarakat yang menjunjung tinggi iffah akan lebih damai. Ketika semua orang saling menjaga adab dan batasan, kepercayaan sosial meningkat, dan kekerasan atau pelecehan bisa ditekan. Dunia yang lebih beradab berawal dari individu-individu yang mau menjaga dirinya.
Pada akhirnya, iffah bukanlah tentang membatasi kebahagiaan, tapi tentang menemukan kebahagiaan yang sejati — kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi orang lain, tapi bersumber dari rasa hormat terhadap diri sendiri. Itulah keindahan sejati yang banyak orang cari, tapi sering salah arah dalam mencapainya.
Jadi, jangan pernah merasa kecil karena memilih menjaga iffah. Justru di dunia yang sering melupakan kehormatan, orang-orang seperti kita lah yang memegang kunci masa depan yang lebih indah. Pelan-pelan, dengan langkah kecil setiap hari, kita bisa tetap menjaga diri, menjaga hati, dan menemukan keindahan yang sebenarnya dalam perjalanan hidup ini.
Ruang Sujud
Kekuatan Iffah: Mengapa Menjaga Diri Adalah Cermin Kemuliaan
Published
23 hours agoon
17/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Di dunia yang semakin cepat berubah ini, banyak orang berpikir bahwa ukuran kesuksesan adalah seberapa populer, kaya, atau berpengaruh seseorang. Tapi seringkali kita lupa, ada satu kekuatan yang jauh lebih mulia dan langka: iffah, kemampuan untuk menjaga kehormatan diri. Ia adalah cermin kemuliaan sejati, yang tidak bisa dibeli dengan uang atau ketenaran.
Iffah berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri, menjaga martabat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Dalam Islam, iffah dianggap sebagai salah satu akhlak terpuji yang menjadi tanda kematangan iman seseorang. Rasulullah ﷺ sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kehormatan dirinya, bahkan jauh sebelum diangkat menjadi Nabi.
Apa yang membuat iffah begitu istimewa? Karena menjaga diri bukan perkara mudah. Menahan lisan dari ucapan buruk, menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, mengontrol hawa nafsu ketika peluang maksiat terbuka lebar — semua itu butuh kekuatan jiwa yang luar biasa. Dan di situlah letak kemuliaannya: orang yang mampu mengendalikan dirinya menunjukkan bahwa ia telah memenangkan salah satu perang terbesar dalam hidup, yaitu perang melawan hawa nafsu.
Dalam kehidupan modern, iffah menjadi semacam perisai yang melindungi seseorang dari kehancuran moral. Ketika segala sesuatu ditawarkan dengan bebas — mulai dari konten vulgar, hubungan tanpa batas, sampai gaya hidup konsumtif tanpa kendali — orang yang memiliki iffah tetap bisa berdiri tegak. Ia tahu batasannya, dan tidak tergoda oleh tren sesaat yang justru bisa merusak dirinya dalam jangka panjang.
Menariknya, iffah bukan hanya soal hubungan laki-laki dan perempuan, walaupun itu bagian penting. Iffah juga menyentuh soal integritas saat bekerja, kejujuran dalam berdagang, kesopanan dalam berbicara, dan bahkan sikap hemat dalam mengelola harta. Singkatnya, iffah adalah gaya hidup yang penuh kesadaran dan kehormatan di setiap aspek kehidupan.
Banyak orang mengira bahwa menjaga diri berarti hidup dalam keterbatasan dan kekakuan. Padahal, iffah justru membuat seseorang menjadi pribadi yang bebas — bebas dari perbudakan nafsu, bebas dari tekanan sosial, dan bebas dari rasa malu di hadapan Allah dan sesama manusia. Orang yang ber-iffah berjalan dengan kepala tegak, karena ia tahu bahwa ia hidup dengan prinsip yang mulia.
Sejarah Islam dipenuhi dengan kisah-kisah inspiratif tentang kekuatan iffah. Salah satunya adalah kisah Yusuf ‘alaihissalam, yang menolak ajakan Zulaikha meskipun secara manusiawi godaan itu sangat berat. Dengan penuh keteguhan, Yusuf memilih dipenjara daripada harus mengkhianati prinsip kehormatan dirinya. Allah pun memuliakannya, menjadikannya salah satu sosok yang dihormati di dunia dan akhirat.
Dalam konteks sehari-hari, iffah bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menjaga lisan dari bergosip, menahan tangan dari mengetik komentar jahat di media sosial, memilih tontonan yang bersih, atau menjaga diri dari gaya hidup pamer kekayaan. Setiap tindakan kecil itu membangun kekuatan besar dalam diri: kekuatan untuk tetap menjadi manusia terhormat di tengah dunia yang sering mengajak kita untuk melupakan nilai-nilai luhur.
Tentu saja, membangun iffah tidak bisa instan. Ia perlu dilatih, diuji, dan dipelihara setiap hari. Ada kalanya kita tergoda, jatuh, atau lengah. Tapi bukan berarti kita gagal. Setiap upaya untuk bangkit lagi, setiap niat untuk kembali menjaga kehormatan diri, adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang mulia.
Salah satu cara terbaik untuk menjaga iffah adalah dengan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Ketika kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita, bahkan saat tak ada manusia lain yang melihat, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Shalat, membaca Al-Qur’an, memperbanyak doa, dan mengingat kematian — semua itu membantu kita menjaga kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya soal dunia, tapi juga soal mempertanggungjawabkan setiap pilihan kita di hadapan Sang Pencipta.
Lingkungan juga sangat berpengaruh. Berada di tengah orang-orang yang menghargai nilai iffah akan membuat kita lebih kuat dalam menjaganya. Sebaliknya, bergaul dengan lingkungan yang permisif terhadap perilaku buruk bisa perlahan-lahan merusak benteng kehormatan kita tanpa kita sadari.
Pada akhirnya, iffah adalah tentang membangun harga diri sejati. Bukan harga diri yang dibangun dari pencitraan atau pencapaian kosong, tapi harga diri yang lahir dari kejujuran, kesucian niat, dan keteguhan hati. Dan menariknya, orang-orang yang menjaga iffah sering kali lebih dihormati, lebih tenang, dan lebih bahagia dalam hidupnya, karena mereka hidup sesuai dengan prinsip yang mulia.
Menjaga diri adalah pilihan berat di dunia yang penuh godaan, tapi justru itulah yang membuatnya menjadi bentuk kemuliaan yang tinggi. Bukan semua orang bisa, tapi siapa pun yang berusaha akan merasakan keindahan dan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh popularitas atau kekayaan.
Maka, mari kita jadikan iffah sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Bukan hanya sebagai slogan, tapi sebagai karakter sejati yang membentuk siapa diri kita, hari ini dan di masa depan.
Ruang Sujud
Iffah: Menjaga Kehormatan Diri dalam Kehidupan Modern
Published
1 day agoon
17/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Di tengah dunia modern yang serba terbuka dan serba cepat ini, menjaga kehormatan diri atau iffah sering kali terasa seperti tantangan besar. Segala sesuatu bisa diakses dalam hitungan detik, informasi mengalir deras tanpa filter, dan budaya populer seolah mendorong kita untuk lebih bebas tanpa batas. Lalu, di mana posisi iffah hari ini? Apakah konsep ini masih relevan, atau justru semakin penting untuk dipertahankan?
Secara sederhana, iffah adalah menjaga diri dari segala hal yang merendahkan harga diri dan kehormatan, baik dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Ini bukan hanya soal menahan diri dari perbuatan buruk, tapi lebih luas: iffah mencakup kesadaran untuk hidup dengan prinsip, integritas, dan rasa malu yang positif. Dalam Islam, iffah adalah bagian dari akhlak mulia, bahkan Rasulullah ﷺ sendiri mengajarkan bahwa menjaga kehormatan diri adalah bagian dari iman.
Di zaman sekarang, ketika batasan antara yang privat dan publik semakin kabur, iffah menjadi tameng yang menjaga seseorang tetap bermartabat. Misalnya, dalam penggunaan media sosial. Kita sering melihat bagaimana orang mudah sekali mengumbar hal-hal pribadi demi validasi atau popularitas sesaat. Padahal, mempertahankan iffah mengajarkan kita untuk selektif: mana yang layak dibagikan, mana yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri.
Bukan berarti orang yang menjaga iffah harus menjadi sosok kaku dan tertutup. Justru sebaliknya, mereka yang memiliki iffah mampu bergaul, berkontribusi, dan menjadi bagian dari masyarakat tanpa kehilangan prinsip. Mereka bisa beradaptasi dengan dunia modern, tanpa harus larut dalam arus negatifnya. Mereka tetap bisa tampil percaya diri, aktif, dan produktif, dengan tetap menjaga batasan yang sehat.
Menariknya, konsep iffah ini tidak hanya berbicara soal hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, walaupun itu bagian penting. Iffah juga menyentuh aspek lain, seperti menjaga lisan dari ucapan yang tidak pantas, menjaga mata dari melihat hal-hal yang dilarang, hingga menjaga hati dari keinginan-keinginan yang berlebihan. Dalam konteks kerja, iffah berarti bekerja dengan jujur, tidak mengambil yang bukan haknya, dan menjaga profesionalitas.
Salah satu contoh konkret iffah di dunia modern adalah sikap selektif dalam pergaulan. Kita hidup di era jaringan sosial yang luas, di mana bertemu orang baru sangat mudah. Namun, iffah mengajarkan bahwa tidak semua pertemanan membawa kebaikan. Ada kalanya kita harus berani menjaga jarak dari lingkungan yang bisa menggerus nilai-nilai kita. Ini bukan soal merasa lebih baik dari orang lain, tetapi soal menjaga diri agar tetap berada di jalur yang benar.
Lalu, bagaimana cara membangun dan mempertahankan iffah dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu kuncinya adalah dengan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Kesadaran bahwa kita selalu dalam pengawasan-Nya membuat kita lebih hati-hati dalam bertindak. Selain itu, membiasakan diri membaca Al-Qur’an, memperdalam ilmu agama, serta mencari lingkungan yang mendukung nilai-nilai kebaikan sangat membantu.
Selain aspek spiritual, penting juga untuk memperkuat mental dan karakter. Dunia modern sering kali menawarkan godaan dalam bentuk yang sangat menarik, dari budaya hedonisme, konsumerisme, sampai gaya hidup instan. Dengan mental yang kuat, kita bisa tetap berpegang pada prinsip tanpa merasa minder atau terseret arus. Di sinilah peran iffah terasa sangat nyata: ia menjadi fondasi yang membuat kita tetap kokoh, bahkan ketika dunia di sekitar kita berubah dengan cepat.
Yang tidak kalah penting, iffah juga harus dibarengi dengan kesadaran diri bahwa setiap manusia berharga dan mulia. Ketika seseorang menyadari nilai dirinya, ia akan lebih mudah menjaga kehormatannya. Ia tidak akan sembarangan mengejar pengakuan atau validasi dari orang lain, karena ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh jumlah likes, komentar, atau popularitas dunia maya.
Dalam pandangan Islam, orang yang menjaga iffah akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah SWT. Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaga kehormatannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini adalah janji luar biasa: ketika kita berusaha menjaga diri, Allah sendiri yang akan membantu dan memuliakan kita.
Pada akhirnya, iffah bukanlah konsep kuno yang harus ditinggalkan. Justru di tengah dunia yang semakin bebas ini, iffah adalah pelindung yang membuat kita tetap menjadi manusia yang bermartabat. Menjaga iffah bukan berarti membatasi diri, tetapi justru membebaskan diri dari perbudakan nafsu dan tekanan sosial yang menyesatkan. Ia adalah bentuk kebebasan sejati—bebas untuk tetap menjadi pribadi yang terhormat, kuat, dan mulia.
Maka, mari kita jadikan iffah sebagai bagian dari gaya hidup modern kita. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih bermartabat, seimbang, dan penuh nilai kebaikan.
Ruang Sujud
Mengenal Maqashid Syariah: Tujuan Hakiki di Balik Hukum Islam
Published
2 days agoon
16/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Dalam perbincangan mengenai hukum Islam, istilah maqashid syariah kerap muncul sebagai konsep yang fundamental. Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Dengan memahami maqashid syariah, kita tidak hanya memahami “apa” dan “bagaimana” hukum itu berlaku, tetapi juga “mengapa” hukum tersebut penting bagi kemaslahatan manusia.
Secara etimologis, maqashid berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah berarti jalan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka, maqashid syariah adalah maksud atau tujuan dari ditetapkannya syariat Islam. Konsep ini menegaskan bahwa syariat tidak hadir dalam ruang hampa; ia bukan sekadar perintah atau larangan tanpa makna, tetapi mengandung hikmah besar untuk mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan bagi umat manusia.
Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama klasik yang paling berpengaruh dalam pengembangan konsep maqashid syariah. Menurut beliau, tujuan utama syariah adalah menjaga lima hal pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima hal ini disebut sebagai dharuriyat al-khams, yaitu kebutuhan primer manusia yang harus dijaga untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan harmonis.
1. Menjaga Agama (Hifz al-Din)
Islam sebagai agama memiliki landasan iman dan ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Syariat bertujuan menjaga kemurnian aqidah dan memastikan kebebasan beragama tetap terjaga. Oleh karena itu, kewajiban salat, larangan syirik, dan perlindungan terhadap tempat ibadah merupakan bagian dari realisasi tujuan ini.
2. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)
Kehidupan manusia sangat dihargai dalam Islam. Larangan membunuh, kewajiban qisas, dan aturan dalam peperangan yang menghindari pembunuhan terhadap non-kombatan adalah upaya nyata untuk menjaga jiwa. Bahkan dalam konteks kesehatan, Islam menganjurkan pengobatan dan menjaga tubuh sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan.
3. Menjaga Akal (Hifz al-‘Aql)
Akal adalah anugerah besar dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Karena itu, segala bentuk yang merusak akal seperti minuman keras dan narkotika dilarang keras. Sebaliknya, Islam mendorong pencarian ilmu dan pemikiran rasional dalam memahami alam semesta dan ajaran agama.
4. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)
Syariat Islam menetapkan pernikahan sebagai institusi yang sah dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Larangan zina, hukum waris, dan tanggung jawab keluarga merupakan implementasi dari tujuan ini. Anak-anak juga dilindungi haknya sejak dini agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara fisik dan spiritual.
5. Menjaga Harta (Hifz al-Mal)
Harta dalam Islam diakui sebagai salah satu komponen penting dalam kehidupan. Syariat menetapkan berbagai hukum tentang kepemilikan, transaksi, zakat, dan larangan riba demi menjaga keadilan ekonomi dan mencegah penindasan. Pencurian, korupsi, dan penipuan dilarang karena merusak tatanan sosial dan menimbulkan kesenjangan.
Dalam perkembangan kontemporer, para pemikir Islam seperti Syekh Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda memperluas cakupan maqashid syariah. Mereka menekankan pentingnya maqashid dalam membaca dinamika zaman, seperti hak asasi manusia, keadilan gender, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan maqashid, syariah menjadi lentur dan adaptif tanpa kehilangan esensinya.
Pendekatan maqashid ini juga menjadi jembatan penting antara teks dan konteks. Dalam dunia yang terus berubah, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan pendekatan literal terhadap teks. Maqashid memberikan kerangka pemikiran untuk menimbang maslahat dan mafsadat (kebaikan dan keburukan) dalam menetapkan hukum. Misalnya, dalam kasus pandemi, kebijakan penutupan masjid untuk sementara waktu dapat dibenarkan berdasarkan tujuan menjaga jiwa.
Namun, memahami maqashid tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan nash (teks suci). Pendekatan maqashid harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, dan tidak boleh digunakan untuk melegitimasi kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, pemahaman maqashid memerlukan keluasan ilmu, kejujuran intelektual, dan niat yang tulus untuk mencari ridha Allah.
Sebagai umat Islam, memahami maqashid syariah adalah bagian dari upaya untuk menghayati agama secara lebih mendalam. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya kumpulan aturan, tetapi sistem nilai yang menjunjung tinggi kemaslahatan manusia. Dengan maqashid, kita belajar untuk tidak sekadar patuh pada hukum, tetapi juga memahami jiwa dan tujuannya.
Akhirnya, maqashid syariah menjadi cermin bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin. Ia hadir untuk menjaga, melindungi, dan memuliakan manusia dalam seluruh dimensi kehidupannya—spiritual, fisik, intelektual, sosial, dan ekonomi. Maka, memahami maqashid syariah bukan hanya tugas ulama, tetapi juga panggilan bagi setiap Muslim yang ingin hidup sesuai dengan nilai-nilai ilahiah yang penuh hikmah.
Ruang Sujud
Peran Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial
Published
2 days agoon
16/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah individual, tetapi juga memiliki sistem nilai yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk keadilan sosial. Dalam konteks ini, maqashid syariah atau tujuan-tujuan utama syariat Islam memainkan peran penting sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.
Maqashid syariah secara umum merujuk pada lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima hal ini dikenal sebagai dharuriyat al-khams atau kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi demi tercapainya kemaslahatan. Ketika lima hal ini ditegakkan secara menyeluruh, maka lahirlah sistem sosial yang berkeadilan.
Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam
Keadilan dalam Islam bukan sekadar distribusi kekayaan yang merata, melainkan sebuah tatanan hidup yang menjamin hak-hak dasar manusia dihormati dan dilindungi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…” (QS. An-Nahl: 90). Ini menjadi dasar bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam setiap aspek kebijakan dan hukum Islam.
Dalam maqashid syariah, keadilan sosial terwujud saat setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memperoleh haknya untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, bekerja, beragama, serta dilindungi dari penindasan. Keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga kelima maqashid tersebut, karena di sanalah letak keutuhan martabat manusia.
Menjaga Jiwa dan Akal sebagai Pilar Kemanusiaan
Salah satu bentuk keadilan sosial adalah memastikan setiap orang mendapatkan hak untuk hidup sehat dan berakal. Dalam konteks ini, maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa dan akal. Negara dan masyarakat wajib menjamin akses terhadap layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta edukasi yang layak. Larangan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan zat adiktif adalah bagian dari upaya menjaga jiwa dan akal manusia.
Negara yang menelantarkan rakyatnya dalam hal kesehatan atau membiarkan mereka tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan ilmu, telah gagal menjalankan amanah maqashid syariah. Pendidikan dan kesehatan bukan sekadar fasilitas, melainkan hak dasar yang menjadi pilar utama keadilan sosial.
Menjaga Harta dan Keseimbangan Ekonomi
Dalam maqashid syariah, harta memiliki kedudukan penting. Islam mengakui hak kepemilikan, namun sekaligus menekankan tanggung jawab sosial atas harta yang dimiliki. Keadilan sosial dalam bidang ekonomi terwujud ketika ada mekanisme yang menjamin bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Zakat, infak, sedekah, dan larangan riba adalah instrumen syariah yang bertujuan menciptakan redistribusi kekayaan secara adil.
Di sinilah peran maqashid begitu terasa: ia mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir elit, dan mendorong terciptanya solidaritas sosial. Kewajiban zakat, misalnya, bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga instrumen ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Menjaga Keturunan dan Martabat Sosial
Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, dan maqashid syariah menempatkan perlindungan terhadap keturunan sebagai salah satu tujuannya. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjamin perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Pernikahan, pengasuhan, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian integral dari maqashid menjaga nasab dan martabat manusia.
Dalam masyarakat modern, keadilan sosial juga meliputi perlindungan hukum terhadap eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta penyediaan akses yang sama terhadap layanan pendidikan dan pekerjaan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi gender.
Menjaga Agama dan Kebebasan Berkeyakinan
Keadilan sosial menurut maqashid syariah juga mencakup kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meskipun Islam memiliki hukum-hukum tersendiri, tetapi maqashid mengajarkan toleransi dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Islam tidak memaksakan keyakinan, sebagaimana firman Allah, “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama” (QS. Al-Baqarah: 256).
Negara yang adil adalah negara yang menghormati keyakinan warga negaranya, selama tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks pluralisme, maqashid syariah memberi ruang bagi hidup berdampingan secara damai antar pemeluk agama yang berbeda.
Maqashid sebagai Kompas Etika dalam Kebijakan Publik
Dalam dunia modern, maqashid syariah dapat dijadikan sebagai kerangka moral dan etis dalam perumusan kebijakan publik. Prinsip maqashid tidak hanya relevan di wilayah fikih, tetapi juga dalam bidang-bidang strategis seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, perlindungan lingkungan, dan sistem hukum.
Para ulama kontemporer seperti Jasser Auda bahkan mengembangkan maqashid dalam format yang lebih luas, mencakup nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, maqashid tidak hanya menjadi warisan tradisi, tetapi juga solusi bagi tantangan zaman.
Penutup
Maqashid syariah adalah roh dari hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dalam konteks keadilan sosial, maqashid menjadi panduan yang menuntun umat Islam untuk membangun masyarakat yang manusiawi, adil, dan seimbang. Ia bukan hanya alat untuk memahami hukum, tetapi juga panduan moral dalam menciptakan peradaban yang memberi ruang bagi semua.
Ketika maqashid dijadikan pijakan dalam membangun sistem sosial, maka hukum Islam bukan hanya tampak relevan, tetapi juga transformatif—menghadirkan keadilan yang nyata di tengah dunia yang kompleks dan penuh tantangan.
Ruang Sujud
Maqashid Syariah sebagai Landasan Etika dalam Ekonomi Islam
Published
2 days agoon
16/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Ekonomi Islam bukan hanya sekadar sistem finansial yang melarang riba atau menganjurkan zakat, tetapi sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai moral dan spiritual. Di tengah sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengejar keuntungan tanpa batas, ekonomi Islam hadir dengan pendekatan yang lebih seimbang—mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Semua ini berakar pada satu konsep penting dalam Islam: maqashid syariah.
Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama dari diterapkannya hukum Islam. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks ekonomi Islam, maqashid ini berperan sebagai fondasi etis yang menentukan arah kebijakan, strategi bisnis, hingga perilaku konsumen.
Etika Ekonomi: Lebih dari Sekadar Keuntungan
Dalam sistem kapitalisme, orientasi utama pelaku ekonomi adalah profit maximization atau memaksimalkan keuntungan. Sementara dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan dan keseimbangan lebih dikedepankan. Di sinilah maqashid syariah memainkan peran penting sebagai kompas moral: ia memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat dan tetap berpihak pada kemanusiaan.
Contohnya, maqashid menjaga harta (hifz al-mal) bukan hanya berarti menghormati kepemilikan individu, tetapi juga mendorong agar kekayaan tidak terpusat pada kelompok tertentu saja. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7: “…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Distribusi Kekayaan dan Prinsip Keadilan
Konsep keadilan dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui sistem distribusi kekayaan yang adil dan merata. Ini tidak berarti setiap orang harus memiliki jumlah kekayaan yang sama, tetapi bahwa setiap individu punya kesempatan dan hak untuk hidup layak. Zakat, infak, dan wakaf menjadi instrumen penting dalam memastikan distribusi ini berjalan.
Zakat, misalnya, bukan hanya ibadah, tapi juga mekanisme distribusi kekayaan. Ia berfungsi sebagai pembersih harta dan sekaligus alat untuk menjaga stabilitas sosial. Ini adalah bentuk konkret dari maqashid dalam konteks menjaga harta sekaligus menjaga jiwa masyarakat miskin agar tidak terlantar dan kehilangan hak dasarnya untuk hidup layak.
Larangan Riba dan Perlindungan Konsumen
Salah satu bentuk nyata dari penerapan maqashid dalam ekonomi Islam adalah larangan riba. Riba merusak keseimbangan ekonomi karena menindas pihak yang lemah secara finansial dan memperkaya pemilik modal tanpa usaha produktif. Larangan riba sejalan dengan maqashid menjaga harta dan jiwa, karena mencegah eksploitasi ekonomi dan potensi kehancuran finansial bagi individu atau masyarakat.
Selain riba, praktik spekulatif berlebihan (gharar) juga dilarang dalam Islam. Hal ini demi menjaga transparansi dan perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi. Dalam Islam, transaksi yang adil, jelas, dan saling menguntungkan menjadi syarat sahnya akad. Maka dari itu, maqashid menjaga akal dan harta tercermin dalam mekanisme perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah yang lebih transparan dan berbasis prinsip syariah.
Etika Produksi dan Konsumsi
Dalam maqashid syariah, aktivitas ekonomi seperti produksi dan konsumsi tidak bebas nilai. Segala bentuk produksi harus memperhatikan kemaslahatan umat dan tidak merusak lingkungan atau menciptakan kemudaratan. Produk yang haram atau membahayakan kesehatan dilarang, karena bertentangan dengan maqashid menjaga jiwa dan akal.
Begitu pula dalam konsumsi, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan. Tidak boros, tapi juga tidak kikir. “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.” (QS. Al-A’raf: 31). Gaya hidup konsumtif yang mendorong seseorang hidup di luar batas kemampuannya justru merusak tatanan ekonomi dan sosial. Maka, maqashid hadir untuk menyeimbangkan antara hak menikmati dunia dan tanggung jawab sosial terhadap sesama.
Peran Negara dan Kebijakan Publik
Dalam skala lebih besar, maqashid syariah menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan ekonomi publik. Negara yang menjalankan ekonomi Islam seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga, terutama kelompok miskin dan rentan. Subsidi kebutuhan pokok, pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja adalah bagian dari manifestasi maqashid dalam kebijakan negara.
Negara juga wajib mengawasi pasar agar tidak terjadi praktik monopoli, penimbunan, atau manipulasi harga yang merugikan masyarakat. Ini selaras dengan prinsip Islam dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah kedzaliman dalam transaksi.
Maqashid sebagai Kerangka Berpikir Dinamis
Salah satu kekuatan maqashid adalah fleksibilitas dan relevansinya dalam menjawab tantangan zaman. Para pemikir kontemporer seperti Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistemik terhadap maqashid yang mencakup aspek kebebasan, keadilan, pembangunan berkelanjutan, hingga hak asasi manusia. Dalam ekonomi, ini memberi ruang untuk inovasi dan adaptasi dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan modern, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam.
Penutup
Maqashid syariah bukan hanya sekadar teori dalam buku fikih, tetapi panduan etis dan moral yang hidup dalam seluruh aspek ekonomi Islam. Ia memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi membawa maslahat, menjauhkan dari kerusakan, dan menjaga hak-hak dasar manusia.
Dengan menjadikan maqashid sebagai landasan etika ekonomi, Islam menunjukkan bahwa spiritualitas dan keadilan bisa berjalan seiring. Ia bukan sistem yang utopis, tetapi sistem yang manusiawi—dimana keuntungan, etika, dan keberkahan bisa bersatu dalam harmoni.
Ruang Sujud
Menggali Relevansi Maqashid Syariah di Era Digital
Published
2 days agoon
16/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Di tengah revolusi digital yang kian cepat dan disruptif, umat Islam dihadapkan pada tantangan baru dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan ekonomi, sosial, pendidikan, hingga ibadah. Kemajuan teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, hingga mengakses informasi. Dalam situasi yang terus berubah ini, maqashid syariah hadir sebagai kompas moral dan nilai dasar Islam yang tetap relevan, bahkan sangat dibutuhkan, untuk menjaga arah kehidupan tetap sesuai dengan tuntunan syariat.
Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam, yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima tujuan ini bukan sekadar prinsip normatif, melainkan kerangka etis yang membumi dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi zaman, termasuk era digital yang kompleks dan serba cepat ini.
Menjaga Agama di Tengah Banjir Informasi
Salah satu ciri utama era digital adalah banjir informasi. Internet menawarkan akses tanpa batas terhadap berbagai macam konten, mulai dari ilmu pengetahuan hingga hiburan. Namun, tidak sedikit pula konten yang menyesatkan, provokatif, atau bahkan mengandung penodaan agama.
Di sinilah maqashid menjaga agama menjadi penting. Umat Islam harus memiliki literasi digital yang baik agar dapat membedakan antara informasi yang benar dan hoaks, antara dakwah yang mencerahkan dan konten yang justru memecah belah. Para dai dan ulama juga dituntut untuk berdakwah melalui platform digital agar nilai-nilai Islam tetap hadir di ruang publik virtual.
Menjaga Jiwa di Dunia yang Penuh Tekanan
Era digital memberi kemudahan luar biasa, tetapi juga membawa tekanan mental dan sosial yang tak kalah besar. Budaya media sosial mendorong manusia untuk terus membandingkan hidupnya dengan orang lain, yang sering kali berujung pada kecemasan, iri hati, dan depresi.
Konsep hifz al-nafs (menjaga jiwa) dalam maqashid mengajarkan bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga fisik. Islam mengajarkan keseimbangan, ketenangan, dan kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Dalam konteks digital, ini berarti bijak menggunakan media sosial, tidak larut dalam budaya FOMO (Fear of Missing Out), dan mengatur waktu agar tidak kecanduan layar.
Menjaga Akal dalam Arus Disinformasi
Maqashid syariah juga menekankan pentingnya menjaga akal (‘aql). Di era digital, menjaga akal berarti membentengi diri dari informasi yang menyesatkan, teori konspirasi, dan radikalisme berbasis dunia maya. Banyak generasi muda yang menjadi korban indoktrinasi online karena kurangnya literasi kritis.
Oleh karena itu, pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam menjadi sangat penting. Teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas berpikir dan nalar ilmiah, bukan sebaliknya. Penggunaan platform e-learning, aplikasi pembelajaran Islam, hingga AI berbasis dakwah bisa menjadi sarana memperkuat akal umat di era ini.
Menjaga Keturunan dan Etika Digital
Di dunia digital, ancaman terhadap moral generasi muda datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pornografi, cyberbullying, hingga penyimpangan perilaku akibat konsumsi konten bebas yang tak terkendali. Dalam konteks ini, maqashid menjaga keturunan (hifz al-nasl) sangat relevan.
Orang tua dan pendidik memiliki peran krusial dalam membekali anak-anak dengan nilai-nilai Islam sejak dini, termasuk dalam mengajarkan etika berinternet. Pengawasan terhadap konten yang dikonsumsi anak, serta pembiasaan terhadap penggunaan media digital secara sehat dan produktif, adalah bagian dari usaha menjaga maqashid dalam kehidupan modern.
Menjaga Harta: Etika Finansial di Dunia Digital
Ekonomi digital membuka banyak peluang, tapi juga tantangan besar. Investasi online, kripto, NFT, dan berbagai skema bisnis digital lainnya sering kali menjerumuskan banyak orang dalam praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), hingga penipuan.
Maqashid menjaga harta (hifz al-mal) mendorong umat Islam untuk berhati-hati dalam bertransaksi, memastikan setiap aktivitas ekonomi sesuai prinsip halal dan toyyib. Ekonomi digital yang sesuai dengan maqashid harus didorong melalui inovasi keuangan syariah digital, seperti fintech halal, zakat online, dan dompet digital berbasis syariah.
Teknologi untuk Maslahat: Inovasi Sesuai Maqashid
Alih-alih menjadi tantangan semata, teknologi digital sebetulnya bisa menjadi alat untuk mewujudkan maqashid syariah secara lebih efektif. Aplikasi pengingat waktu salat, marketplace halal, platform zakat online, hingga pemanfaatan big data untuk distribusi bantuan sosial adalah contoh bagaimana teknologi bisa menjadi sarana maslahat umat.
Namun tentu saja, semua itu harus dikembangkan dengan niat yang benar dan arah yang sesuai maqashid. Di sinilah pentingnya peran ulama, akademisi, dan profesional Muslim dalam menciptakan ekosistem digital yang islami—bukan hanya dalam kontennya, tapi juga dalam arsitektur dan nilainya.
Penutup: Maqashid sebagai Kompas Digital
Era digital adalah era penuh peluang, tetapi juga penuh jebakan. Agar tidak tersesat, umat Islam memerlukan kompas nilai yang kokoh. Maqashid syariah adalah panduan itu—ia memberi arah bagi setiap aktivitas digital agar tetap berada dalam koridor Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Dengan memahami dan menerapkan maqashid secara kontekstual, umat Islam bisa tetap relevan dan unggul di tengah perubahan zaman, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur syariat.
Ruang Sujud
Istihza’ dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Besar dan Ancaman Aqidah
Published
3 days agoon
15/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Dalam kehidupan sosial yang kompleks dan penuh perbedaan, sikap saling menghormati menjadi kunci harmoni. Namun tak jarang, kita menjumpai perilaku yang justru bertentangan dengan nilai tersebut—seperti istihza’, yaitu mengejek atau memperolok hal-hal yang dianggap suci dalam Islam. Dalam pandangan syariat, istihza’ bukan hanya bentuk keburukan akhlak, tapi bisa menjadi ancaman serius terhadap keimanan seorang muslim.
Apa Itu Istihza’?
Secara bahasa, istihza’ berasal dari kata hazaa-a yang berarti mengejek, memperolok, atau merendahkan sesuatu dengan maksud menghina. Dalam konteks Islam, istihza’ merujuk pada tindakan meremehkan atau mempermainkan ajaran agama, baik itu Al-Qur’an, hadis, Allah, Rasul-Nya, syariat, maupun simbol-simbol keagamaan lainnya.
Istihza’ bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ucapan yang mengejek ajaran agama, mimik wajah yang menghina praktik keislaman, bahkan konten humor atau meme yang menyindir simbol-simbol Islam secara tidak pantas. Meskipun kadang dikemas dalam bentuk candaan, tindakan ini tetap dianggap serius dalam Islam.
Dalil dan Penegasan dalam Al-Qur’an
Al-Qur’an secara tegas mencela perilaku istihza’. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 65-66:
“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka katakan), niscaya mereka akan menjawab: ‘Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.’ Katakanlah: ‘Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?’ Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman.”
Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok munafik yang mengejek Rasulullah dan para sahabat. Mereka beralasan bahwa apa yang mereka katakan hanyalah candaan, namun Allah menegaskan bahwa ejekan terhadap agama tidak bisa dianggap sepele. Bahkan, Allah menyatakan bahwa tindakan tersebut bisa menggugurkan keimanan seseorang.
Hukum Istihza’ dalam Islam
Mayoritas ulama sepakat bahwa istihza’ terhadap Allah, Rasul, Al-Qur’an, ataupun syariat Islam termasuk kufur akbar, yakni kekafiran besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi dari tindakan istihza’, meskipun pelakunya tidak berniat untuk keluar dari Islam.
Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa memperolok agama, baik dengan sungguh-sungguh maupun dalam bentuk candaan, tetap masuk dalam kategori kekufuran. Karena dalam hal ini, niat tidak menjadi pertimbangan utama—yang dilihat adalah objek dan substansi olok-oloknya.
Bentuk-Bentuk Istihza’ di Era Modern
Di zaman media sosial, istihza’ bisa menyebar dalam bentuk konten viral yang tampak lucu namun sebenarnya merendahkan agama. Contohnya adalah meme yang memperolok bacaan shalat, video yang menertawakan adzan, atau candaan tentang hukum-hukum fikih. Ironisnya, hal ini sering kali dikonsumsi oleh umat Islam sendiri tanpa kesadaran akan bahayanya.
Tak hanya itu, sebagian orang yang merasa ‘bebas berekspresi’ juga berani menyampaikan kritik terhadap agama dengan nada ejekan, seperti mempertanyakan ajaran poligami, jihad, atau jilbab dengan nada sinis dan menyudutkan. Kritik semacam ini bisa berubah menjadi istihza’ jika dilakukan dengan niat merendahkan dan memperolok.
Mengapa Istihza’ Berbahaya?
Istihza’ merusak dua hal penting dalam Islam: adab dan akidah. Dari sisi adab, mengejek hal-hal suci menunjukkan hilangnya rasa hormat terhadap sesuatu yang seharusnya diagungkan. Dari sisi akidah, istihza’ dapat menjadi tanda lemahnya iman, bahkan indikasi kemunafikan.
Lebih dari itu, istihza’ memiliki efek sosial yang destruktif. Ia bisa memicu kebencian antarumat beragama, memunculkan ketegangan sosial, dan membentuk opini negatif terhadap Islam. Maka, menjaga lisan dan etika komunikasi adalah bagian dari menjaga stabilitas sosial dan harmoni antarumat manusia.
Solusi dan Sikap Seorang Muslim
Seorang muslim hendaknya memiliki ghirah (kecemburuan) terhadap agamanya. Ketika mendengar ada yang mengejek ajaran Islam, ia tidak boleh diam atau ikut-ikutan. Sikap yang tepat adalah menegur dengan bijak, menjelaskan dengan hikmah, dan jika tidak mampu, maka menjauh dari majelis tersebut sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an:
“Dan sungguh, Dia telah menurunkan kepada kamu di dalam Kitab (Al-Qur’an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain.” (QS. An-Nisa: 140)
Selain itu, penting bagi para dai, guru, dan pembina umat untuk menyampaikan pendidikan akidah dan adab kepada generasi muda. Media sosial harus dijadikan ruang edukasi, bukan ruang olok-olokan terhadap ajaran agama.
Penutup
Istihza’ bukanlah sekadar candaan atau ekspresi bebas. Dalam Islam, istihza’ adalah tindakan yang sangat serius karena menyangkut kehormatan agama, kebenaran wahyu, dan akidah seorang muslim. Setiap individu dituntut untuk menjaga lisannya, menghormati hal-hal yang suci, dan tidak menjadikan ajaran agama sebagai bahan olok-olokan. Sebab dalam pandangan Islam, iman dan ejekan terhadap agama tidak akan pernah bisa berdampingan.
Ruang Sujud
Mengapa Istihza’ Terhadap Ajaran Islam Bisa Menggugurkan Iman?
Published
3 days agoon
15/04/2025By
Yusuf Hasyim
Monitorday.com – Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai candaan, sindiran, bahkan hinaan yang ditujukan pada ajaran agama. Tak jarang, hal itu dianggap biasa atau bahkan lucu oleh sebagian orang. Namun dalam Islam, tindakan seperti ini dikenal sebagai istihza’, yaitu mengejek hal-hal suci dalam agama. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perbuatan ini bukan sekadar dosa besar, melainkan dapat menggugurkan iman seseorang.
Definisi Istihza’ dalam Islam
Istihza’ secara bahasa berarti ejekan, olok-olok, atau mempermainkan. Dalam konteks syariat Islam, istihza’ adalah sikap memperolok ajaran agama, seperti menghina Allah, Rasulullah, Al-Qur’an, hadis, hukum Islam, atau syiar-syiar lainnya. Perilaku ini bisa dilakukan lewat ucapan, tindakan, tulisan, gambar, atau bahkan hanya dengan ekspresi wajah.
Yang menjadikan istihza’ sangat berbahaya adalah karena ia bukan hanya merusak adab, tapi juga merusak akidah. Orang yang melakukan istihza’ bisa tergelincir dalam kekafiran meski sebelumnya telah beriman.
Dalil Al-Qur’an: Ancaman Tegas bagi Pelaku Istihza’
Al-Qur’an mengabadikan kejadian yang menjadi peringatan keras bagi umat Islam agar tidak meremehkan ajaran agama. Dalam Surah At-Taubah ayat 65-66, Allah berfirman:
“Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman.”
Ayat ini turun ketika sekelompok munafik memperolok Nabi Muhammad dan para sahabatnya, lalu mereka berdalih bahwa ucapan mereka hanyalah gurauan. Namun Allah menolak alasan tersebut dan langsung menyatakan bahwa tindakan mereka adalah bentuk kekafiran yang menggugurkan keimanan mereka.
Ayat ini menjadi dalil utama bahwa istihza’ terhadap ajaran Islam adalah perbuatan kufur meskipun pelakunya menganggap itu hanya candaan.
Mengapa Bisa Membatalkan Iman?
Iman tidak hanya sekadar percaya dalam hati, tetapi juga menghormati dan membela ajaran agama. Ketika seseorang memperolok sesuatu yang suci, berarti ia telah merendahkan dan tidak mengagungkan agama sebagaimana mestinya. Ini bertentangan dengan esensi keimanan.
Ulama menegaskan bahwa menghina Allah, Rasul, atau Al-Qur’an secara sadar dan sengaja adalah bentuk keluar dari Islam, walaupun tidak diiringi dengan niat murtad. Karena dalam perkara ini, niat tidak lagi menjadi ukuran utama, melainkan objek dan substansi dari ejekan itu sendiri.
Imam Ibn Hazm berkata, “Setiap orang yang mengejek Allah, atau satu ayat dari Kitab-Nya, atau satu hukum dari hukum-Nya, maka dia telah kafir dengan sebenar-benarnya kufur, dan keluar dari agama.”
Contoh-Contoh Istihza’ yang Sering Diabaikan
Ada banyak contoh istihza’ yang muncul dalam kehidupan modern, dan sering kali dianggap sepele:
Membuat lelucon tentang surga dan neraka.
Menyindir ajaran Islam seperti hijab, zakat, atau jihad dengan nada merendahkan.
Mengolok-ngolok suara imam saat shalat.
Membuat meme yang mempermainkan ayat Al-Qur’an atau hadis Nabi.
Berkata sinis, “Kalau Islam mengatur segalanya, kenapa umat Islam tertinggal?”
Contoh-contoh ini mungkin dikemas dengan niat bercanda, tetapi dalam pandangan syariat, itu tetap bisa termasuk istihza’ yang membatalkan keimanan, apalagi jika dilakukan secara terang-terangan dan berulang.
Sikap Islam terhadap Candaan
Islam bukan agama yang kaku dan anti-humor. Rasulullah sendiri dikenal suka bercanda, namun tidak pernah berdusta dan tidak pernah menjadikan agama sebagai bahan lelucon. Candaan beliau selalu dalam batas kebenaran dan tidak merendahkan siapa pun, apalagi agama.
Dalam hadis, Rasulullah bersabda:
“Sesungguhnya aku bercanda, tapi aku tidak mengatakan kecuali yang benar.” (HR. Tirmidzi)
Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, humor diperbolehkan selama tidak mengandung kebohongan, penghinaan, atau pelecehan terhadap ajaran agama.
Bagaimana Jika Sudah Terlanjur Melakukan Istihza’?
Jika seseorang pernah melakukan istihza’, baik secara sadar maupun karena ketidaktahuan, maka yang harus dilakukan adalah:
1. Segera bertaubat dengan taubat nasuha.
2. Mengucapkan kembali dua kalimat syahadat, karena ia telah tergelincir dalam kekafiran.
3. Menyesali perbuatan tersebut dan bertekad tidak mengulanginya lagi.
4. Menjaga lisan dan sikap agar tidak terjerumus dalam perbuatan serupa.
Jangan meremehkan ucapan yang tampaknya kecil. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:
“Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan suatu perkataan yang ia anggap remeh, namun perkataan itu menyebabkan ia tergelincir ke dalam neraka selama tujuh puluh tahun.”
Menjaga Iman di Era Media Sosial
Di era digital ini, batas antara hiburan dan penghinaan sering kali kabur. Banyak konten viral yang mengandung unsur istihza’, dan umat Islam dituntut lebih bijak dalam memilah dan menyikapi. Jangan hanya karena ingin lucu atau mengikuti tren, lalu tanpa sadar ikut menyebarkan konten yang merendahkan agama sendiri.
Maka dari itu, menjaga iman bukan hanya soal ibadah pribadi, tapi juga soal menjaga lisan, tulisan, dan postingan dari hal-hal yang merendahkan Islam. Ingatlah bahwa iman bisa runtuh hanya dengan satu ejekan yang dianggap sepele.
Penutup
Istihza’ terhadap ajaran Islam adalah perbuatan sangat berbahaya yang bisa menggugurkan iman. Dalam Islam, iman bukan hanya diyakini dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam sikap penghormatan terhadap agama. Siapa pun yang mempermainkan ajaran Islam, baik lewat ucapan, tindakan, maupun candaan, berarti telah merusak fondasi keimanan itu sendiri.
Karenanya, seorang muslim harus berhati-hati, menjaga lisan dan perilaku, serta menjauhkan diri dari konten atau pergaulan yang menjadikan agama sebagai bahan ejekan. Iman itu mahal, dan tidak layak ditukar dengan candaan sesaat.
Monitor Saham BUMN

Duh! Hakim AS Putuskan Google Bersalah Gegara Kasus Ini

Damai yang Membunuh Palestina

Derby Korea Batal Terjadi di Final Piala Asia U-17 2025, Penakluk Indonesia Keok

Comeback Gila MU Bikin Old Trafford Bergemuruh, Amorim Sindir Suporter yang Balik Duluan

Pesan Wamendikdasmen Saat Melepas 1.500 Lulusan SMK Siap Kerja ke LN

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Mendikdasmen Wajibkan Guru Ikuti Pelatihan Rutin

MUI dan Tokoh Lintas Agama Sikapi Rencana Evakuasi Penduduk Gaza

Menlu RI dan AS Sepakat Perluas Kemitraan Strategis

Prabowo Siapkan Langkah Strategis untuk Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

Mensos: Guru Sekolah Rakyat Diprioritaskan dari PNS dan PPPK

Iffah: Pilar Kekuatan Spiritual dalam Islam

Tertinggal dari Marquez, Manajer Ducati Soroti Masalah Mental Bagnaia

Timnas Indonesia Tak Kirim Pemain Kunci di Duel ASEAN All-Stars vs MU, Lha Kenapa?

Islamophobia Menguat di Dunia, MUI Sampaikan 8 Poin Rekomendasi

Iffah dalam Kehidupan Sehari-hari: Menemukan Keindahan dalam Menjaga Diri

Pemprov Jawa Barat Resmi Larang Masjid Minta Sumbangan Di Tengah Jalan

S3 Bukan Sekadar Gelar, Tapi Lompatan Hidup! Ini Alasannya!

Kekuatan Iffah: Mengapa Menjaga Diri Adalah Cermin Kemuliaan

Guru Besar Universitas Indonesia Serukan Masyarakat Bela Palestina Dengan Jiwa