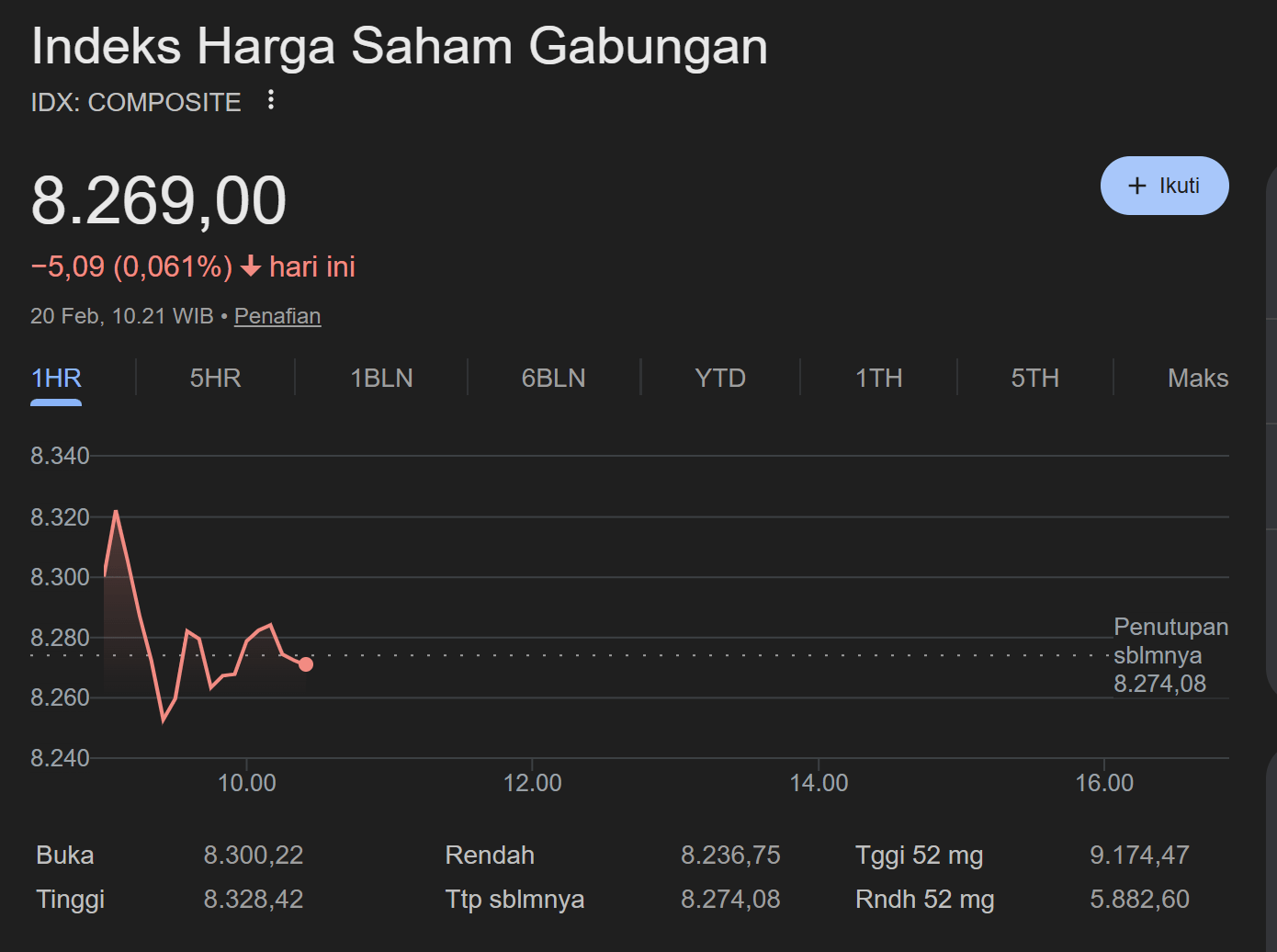“Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar…” (QS. Al-Baqarah: 187).
Ayat ini kerap kita pahami sebatas batas waktu sahur. Padahal, di dalamnya tersimpan satu pesan yang lebih dalam: Al-Qur’an mengatur ritme makan manusia. Ada waktu makan—malam hingga fajar. Ada waktu berhenti—sepanjang siang. Pola ini bukan sekadar aturan ibadah, melainkan desain biologis yang selaras dengan cara kerja tubuh.
Selama sebelas bulan, banyak orang makan tanpa pola. Sarapan tergesa, makan siang terlambat, camilan tak terhitung, kopi berulang kali. Sistem pencernaan bekerja hampir tanpa jeda. Ramadan datang seperti tombol “reset”. Tubuh dipaksa berhenti menerima asupan selama lebih dari 12 jam. Dan menariknya, tubuh tidak panik.
Perubahan sistem pencernaan saat puasa justru menunjukkan kecerdasan biologis yang luar biasa. Ketika tidak ada makanan masuk, lambung menurunkan produksi asamnya. Ini penting untuk mencegah iritasi pada dinding lambung. Dalam kondisi normal, asam lambung diproduksi untuk membantu mencerna makanan. Namun saat tidak ada yang perlu dicerna, produksinya ikut melambat. Puasa, dalam batas wajar, memberi kesempatan lambung beristirahat.
Pankreas pun ikut menyesuaikan diri. Tanpa asupan gula, produksi insulin menurun. Tubuh lalu mengalihkan sumber energi ke cadangan glikogen yang tersimpan di hati. Liver bekerja memecah simpanan tersebut menjadi energi. Inilah sebabnya kita tetap mampu beraktivitas, berpikir, bahkan bekerja produktif selama berpuasa. Tubuh dirancang untuk menghadapi fase tanpa makan secara periodik.
Usus halus dan usus besar juga mengalami adaptasi. Karena sedikit makanan yang masuk, proses penyerapan nutrisi berhenti sementara. Gerakan peristaltik melambat. Usus besar menyerap air lebih efisien untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Semua berlangsung dalam koordinasi yang rapi. Puasa pada dasarnya adalah jeda metabolik—istirahat alami bagi sistem cerna.
Berbagai studi tentang pola makan periodik atau intermittent fasting menunjukkan bahwa jeda makan memberi dampak positif terhadap sensitivitas insulin dan keseimbangan metabolik. Meski konteksnya berbeda dengan puasa Ramadan yang sarat dimensi spiritual, prinsip biologisnya serupa: tubuh mendapat waktu untuk melakukan penataan ulang.
Namun manfaat puasa bagi kesehatan pencernaan sering kali terganggu oleh satu hal: cara berbuka.
Setelah hampir seharian beristirahat, sistem cerna tidak dirancang untuk menerima makanan berat dalam jumlah besar secara mendadak. Lonjakan gula darah, produksi asam lambung yang tiba-tiba meningkat, serta beban lemak berlebih dapat membuat lambung “terkejut”. Keluhan kembung, nyeri ulu hati, atau rasa tidak nyaman setelah berbuka sering kali bukan disebabkan oleh puasanya, melainkan oleh pola makannya.
Di sinilah etika makan yang diajarkan Islam menemukan relevansinya. Berbuka dengan yang ringan—seperti kurma atau buah—memberi transisi lembut bagi sistem cerna. Mengunyah perlahan bukan sekadar adab, tetapi mekanisme biologis untuk membantu pencernaan bekerja optimal. Memberi jeda sebelum makan besar memungkinkan lambung menyesuaikan kembali ritmenya.
Asupan serat juga menjadi kunci. Makanan tinggi serat membantu pergerakan usus tetap lancar, mencegah sembelit, dan meringankan kerja saluran cerna. Dalam konteks puasa, nutrisi seimbang—karbohidrat kompleks, protein cukup, lemak sehat, serat, dan cairan memadai—menjadi fondasi agar tubuh tidak sekadar “bertahan”, tetapi tetap sehat.
Puasa sejatinya bukan hanya menahan lapar, melainkan melatih keteraturan. Ia menata ulang hubungan manusia dengan waktu, dengan tubuh, dan dengan keinginan. Ketika al-Qur’an mengatur kapan kita makan, sesungguhnya ia sedang mengajarkan disiplin biologis sekaligus spiritual.
Masalahnya, sering kali kita memaknai puasa sebagai penundaan makan, bukan penataan makan. Siang hari menahan diri, malam hari melampiaskan. Padahal tubuh membutuhkan ritme, bukan ekstremitas.
Di ruang sujud, kita belajar tunduk. Di dalam tubuh, organ-organ pun tunduk pada hukum keseimbangan. Puasa menghadirkan jeda yang menyehatkan—asal kita tidak merusaknya dengan ketergesaan dan berlebihan.
Mungkin di sanalah hikmah yang jarang kita renungkan: bahwa ibadah ini bukan hanya membersihkan jiwa, tetapi juga mengajarkan kita mendengar bahasa tubuh—yang sejak awal telah diciptakan selaras dengan wahyu.